 |
| Ilustrasi Perjalanan They Eluay (Ist/Google |
Suva,6/4(Jubi)—Manusia Asli Papua
memang menjadi korban ruang demokrasi Indonesia. Kemerdekaan ialah hak segala
bangsa, setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan
pikiran dan pendapat secara lisan tertulis di muka umum yang dijamin konstitusi
(UUD 1945 alinea pertama dan pasal 28) hanyalah mimpi.
Manusia
Papua harus membayar demokrasi itu dengan darah dan nyawa. Puluhan hingga
ratusan nyawa manusia Papua menjadi taruhan demi kehendak berdemokrasi damai.
Kita bisa membaca catatan contoh kasus manusia Papua menjadi korban emosional
aparat penegak demokrasi Indonesia yang damai.
Pertama, kita ingat tokoh fenomenal penegak
demokrasi Papua Theys H. Eluay. Theys yang memimpin mobilisasi masa manusia
Papua dari 2000 hingga puncaknya pada konggres Papua II harus menjadi korban
penculikan Kopasus (11/11/2001). Pembunuhan Theys, menurut Pdt. Benny Giay,
kematian HAM, alias kematian demokrasi Indonesia di Papua.
Kedua, pembunuhan demokrasi terus
berlanjut.Pada 9 Agustus 2008, penegak demokrasi membubarkan perayaan hari
Internaional Masyarakat Pribumi di Lapangan Sinapu, Wamena. Pembubaran perayaan
itu menyebabkan nyawa Opinus Tabuni melayang akibat tima panas aparat gabungan
Indonesia. Kasus itu masuk ke kantong penegak hukum hingga kini belum jelas
pelakunya.
Ketiga, ingatan kita belum hilang akan
pembunuhan demokrasi. Kita harus berhadapan dengan fakta pembunuhan demokrasi
yang baru. Pada 19 Oktober tahun 2011, penegak demokrasi menembak mati Demianus
Daniel Kadepa, Yakobus Samonsabra, dan Max Asa Yeuw. Mereka menjadi tebusan
ekspresi demokrasi di lapangan Zakeus yang dikenal dengan Konggres Papua III.
Ratusan orang yang lain terluka dan darah pun tertumpah membayar kehendak
berdemokrasi damai itu.
Keempat,
setahun kemudian, pada pertengahan 2012, pasukan terlatih penegak demokrasi
Indonesia kembali menembak mati Mako Tabuni, ketua I Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) dan akhir tahun menembak mati Hubertus Mabel, Komandan Militan
KNPB. Nyawa Mako, Hubertus Mabel dan anggota KNPB lain pun turut menjadi korban
tebusan mobilisasi umum dan damai KNPB yang muncul di Kota Jayapura sejak tahun
2008 hingga meluas ke seluruh tanah Papua.
KNPB belum lunas bayar ruang
demokrasi dengan nyawa Mako Tabuni, Hubertus Mabel dan kawan-kawan mereka. Kita
harus mendengar lagi kabar baru tentang pembunuhan demokrasi di tubuh KNPB pada
akhir 2013. Polisi merasa harus membunuh Matias Tengket lalu di buang ke Danau
Sentani. “Victor Yeimo:Polisi Tembak Mati Matias Tengket dan di Buang ke
Danau,” kata Yeimo kepadatabloidjubi.com (27/11).
Kita
harap, pengalaman kemarin menjadi pelajaran untuk kita menata kehidupan
demokrasi yang lebih baik di tahun 2014. Semua kritikan dan saran terhadap
penegakan demokrasi yang datang pascapembubaran aksi damai berujung pada
pembunuhan aktivis Papua, dan warga sipil pun tidak dihiraukan.
Kita
harus mendengar lagi, di awal tahun, pada 3 April, penegak demokrasi
membubarkan aski mahasiswa yang mendukung aksi aktivis HAM di Eropa yang
menyeruhkan pembebasan TAPOL/NAPOL Papua dan menahan dua aktivis mahasiswa atas
nama Alfares Kapisa dan Yali Wenda. Penegak demokrasi membawa mereka ke kantor
Polresta untuk di minta keterangan terkait aksi namun kenyataan yang mereka
alami kekerasan fisik. Keterangan yang mereka berikan pun tidak terbukti dan
menyeret mereka. Mereka hanya terluka dan darah keduanya pun tidak terbendung,
telah tertumpah membayar aksi demokrasi damai di Jayapura.
Satu hal yang sangat kita sayangkan
adalah darah dan korban nyawa itu, menurut penegak demokrasi Indonesia, karena
korban terlibat dalam pelanggaran demokrasi. Persoalannya polisi tidak pernah
membuktikan pelanggaran atas tuduhan itu dengan pembuktian hukum positif
demokrasi Indonesia. Penegak hukum malah mengunakan kewenangan prosedural
demokrasi represif (menghilangkan fakta) untuk menghalanggi kehendak
berdemokrasi. “Tindakan aparat sesuai prosedur hukum,”tutur para penegak hukum
membenarkan tindakan brutal. (baca:Memoriam Pasionis Papua).
Habis
perkara hadir dengan pernyataan yang sama di kasus lain. Semuanya mandek dan
tidak berkembang. Frasa ‘prosesdur hukum’ memang sangat familiar. Kata itu
membudaya dan warga sipil pun menilai ada aturan penegak hukum harus menghabisi
nyawa manusia yang sangat bertentangan dengan moralitas agama. Moralitas
pengahisan nyawa manusialah yang kita bangun kemudian cita-cita kemerdekaan
ialah hak segala bangsa tereduksi. Karena itu, di Papua, ada istilah ‘latihan
lain, main lain’.
Hukum
bicara lain dengan tindakan pembuat dan pemilik hukumnya. Hukum hanyalah
retorikan mimpi Indonesia yang demokratis. Karena telah menjadi budaya
demokrasi Indonesia, kita telah saksikan dan mendengar kata-kata hingga
tindakan prosedural penegak hukum jauh dari hukumnya. Kata-kata yang sangat
rasis, yang bukan menjadi isu di Papua pun terlontar.
“Sebelum membubarkan demontran,
polisi menyebut monyet,”tulis tabloidjubi.com (2/4) dan melakukan kekerasan
terhadap dua aktivis Papua dan kekerasan terhadap orang Papua telah membudaya
di kalangan penegak demokrasi. Kita harap kata monyet ini tidak membudaya dan
menembah isu pelanggaran terhadap hak pengakuan orang Papua sebagai manusia.
(Baca: “Siapa yang Monyet, Kamu atau Saya”, yang ditulis tabloiidjubi.com(http://tabloidjubi.com/2014/04/03/siapa-yang-monyet-saya-atau-kamu/).
Perbuatan penegak hukum jauh dari
cita-cita hukum itu, menurut filsuf sosial, Fredrich August von Hayek,
komunikasi pengetahuan masa lalu dengan masa kini terputusan. “Penularan
kumpulan pengetahuan kita seiring dengan berjalannya waktu dan komunikasi di
antara orang-orang sesaman tentang informasi menjadi dasar tindakan mereka
terputus atau berjalan dengan kepentingan sepihak,”tulis Hayek kemudian di
kutip Eugene F. Miller dalam bukunya The
Constitutios of Liberty. Putusnya komunikasi pengetahuan mengenai
dasar tindakan anak bangsa memang terlihat mandek dalam pendidikan formal dan
nonormal.
Pendidikan
formal Indonesia sangat menekankan terori tetapi praktek tidak berlanjut.
Praktik yang tidak berlanjut itu kemudian menjadi masalah dalam praktik
demokrasi. Penegak demokrasi dari sipil hingga militer menjalani pendidikan
fisik lebih berat daripada pendidikan mental yang mengandalkan akal budi yang
manusiawi.
Unsur
balas dendam terus membuadaya. Karena itu, konstitusi yang mengajarkan ukuran
demokrasi itu keutuhan manusia, cita-cita bangsa-bangsa di dunia, bagi semua
bangsa dan warga negara diabaikan. Penegak hukum menegakkan demokrasi sangat
buta, parsial dan sangat jauh dari amana konstitusi. Persatuan Indoensia,
(keutuhan manusia) kemanusiaan (penegak hukum dan warga sipil) yang adil dan
beradap menjadi korban. Korban nyawa dan korban luka akibat tindakan demokrasi
yang tidak jelas sumbernya terus menghiasi dan mencidrai negara demokrasi.
Kalau fakta demokrasi berfungsi
sebaliknya, penegak hukum dan anak bangsa sedang merubah hukum demokrasi.
Kemerdekaan ialah menjadi bukan hak segala bangsa dan menjadi kemnusiaan yang
tidakberadap, yang menjadi kenyataan. Bangsa yang biadap dan babar menjadi satu
fakta disamping cita-cita demokrasi yang luhur. Cita-cita luhur terus menjadi
cita tanpa usaha. Kapan cita-cita itu menjadi kenyataan kalau fakta kita
mereduksinya? Apakah fakta ini awal dari kehancuran demokrasi Indonesia? Apakah
fakta korban luka, darah dan nyawa itulah yang menjadi harga demokrasi
Indonesia di Papua? (Jubi/Mawel)
Sumber: tabloidjubi.com








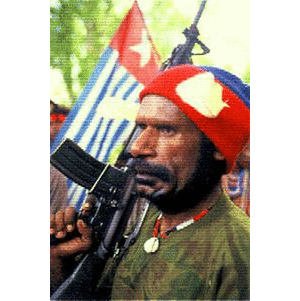






0 komentar:
Posting Komentar